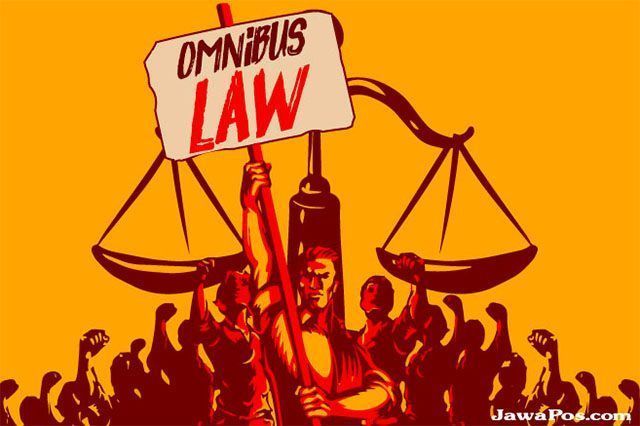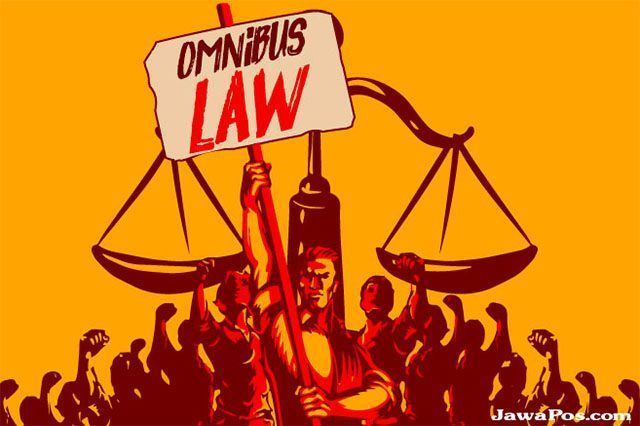
Usulan pemerintah tentang RUU Cipta Kerja telah masuk Prolegnas DPR tahun 2020 dan berproses hingga disahkan. RUU yang memuat 11 klaster masalah, antara lain :
1) Penyederhanaan Perizinan,
2) Persyaratan Investasi,
3) Ketenagakerjaan,
4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM,
5) Kemudahan Berusaha,
6) Dukungan Riset dan Inovasi,
7) Administrasi Pemerintahan,
8) Pengenaan Sanksi,
9) Pengadaan Lahan,
10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
11) Kawasan Ekonomi, telah memicu pro kontra publik sejak awal hingga akhir.
Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang juga populer dengan sebutan Omnibus law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.
Beragam protes dan unjuk rasa yang muncul tidak menyurutkan langkah pemerintahan Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti keputusan DPR dengan menetapkan dalam lembaran negara menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada 2 November 2020.
Keputusan tersebut di satu sisi telah memupus harapan agar pemerintah menolak keputusan DPR dengan menerbitkan Perppu, namun di sisi lain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menolak untuk melakukan langkah perlawanan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Gelombang penolakan muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah serikat buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mensinyalir bahwa UU Cipta Lapangan Kerja mengandung muatan yang dapat merugikan kepentingan pekerja, diantaranya :
1). penghapusan sistem upah minimum dengan pemberlakuan upah per jam;
2). hilangnya pesangon dengan skema pemberian tunjangan Putus Hubungan Kerja (PHK) sebesar 6 bulan upah;
3). perluasan sistem outsourcing yang semula terbatas pada 5 jenis pekerjaan (cleaning services, catering, driver, security dan jasa penunjang);
4). menghilangkan jaminan pensiunan dan jaminan kesehatan sebagai konsekuensi perubahan sistem pengupahan;
5). membuka pintu masuk serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan
6). menghapuskan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan upah pekerja sesuai upah minimum.
Aksi penolakan yang makin meluas telah melibatkan kalangan aktifis mahasiswa di seluruh penjuru tanah air, serta organisasi dan tokoh masyarakat dan akademisi.
Kelompok Cipayung, kumpulan organisasi ekstra kampus secara tegas menolak pengesahan omnibus law dengan alasan bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat.
Sedangkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah menilai pengesahan RUU Cipta Kerja sebagai praktek ketatanegaraan yang buruk dan tidak melalui proses yang partisipatif sesuai aspirasi masyarakat.
Protes dan penolakan yang muncul tentu wajar, apalagi jika dikaitkan dengan berbagai kejanggalan dalam pengesahan di mana sejak disahkan oleh Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 hingga ditetapkan oleh Presiden Jokowi, setidaknya ada beragam versi draft yang telah disahkan yang beredar di masyarakat.
Naskah yang diserahkan DPR kepada Istana sendiri berjumlah 812 halaman, dan kemudian berubah menjadi naskah final versi pemerintah sejumlah 1.187 halaman dengan dalih perubahan format penulisan baku dalam catatan negara. Bahkan, belakangan diketahui oleh publik bahwa “salah ketik” pasal masih terjadi meski RUU tetelah diundangkan.
Sikap pemerintah yang sejak awal terkesan bersikukuh tentu saja memicu tanda tanya tentang apa kepentingan sesungguhnya yang hendak dicapai dan kepentingan siapa yang direpresentasikan oleh pemerintah dan DPR dalam hal omnibus law? Bagi pemerintah, omnibus law adalah jalan paling efektif untuk mengatasi masalah obesitas regulasi dan birokratisasi yang selama ini menjadi hambatan bagi perekonomian, terutama investasi.
Secara faktual harus diakui bahwa obesitas regulasi ini telah menjadi masalah kronis dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Presiden Jokowi menyebut kondisi hiper regulasi di mana sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah telah menyebabkan ruang gerak pemerintah dan dunia usaha menjadi terjebak dalam birokratisasi.
Pernyataan itu sejalan dengan riset PSHK tentang 42.996 regulasi yang terdiri dari peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 15.965 di Indonesia, dimana peraturan terbanyak justru di Eksekutif (Kementerian dan Pemda).
Efisiensi Pasar dan liberalisasi ekonomi
Gagasan pemerintah tentang perlunya omnibus law perlu dilihat dalam kerangka kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan perlunya investasi asing guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Bagi pemerintah, investasi merupakan “resep mujarab” untuk mendongkrak perekonomian, dan itu hanya bisa dilakukan jika “barrier to entry” bagi investasi asing dapat diatasi melalui omnibus law. Persoalan determinasi modal asing sebenarnya bukan isu baru, namun telah menjadi bagian dari empirisme pembangunan di Indonesia.
Para teknokrat Orde Baru berhaluan ekonomi neoklasik yang lazim dikenal dengan istilah “Mafia Berkeley” telah berhasil meyakinkan Orde Baru untuk akomodatif terhadap modal asing dan peranan lembaga donor internasional seperti IMF dan World Bank setelah UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dirilis.
Liberalisasi ekonomi melalui deregulasi juga berlangsung diera 1980-andi mana sektor perbankan memberi kelonggaran bagi modal asing untuk berinvestasi di sektor perbankan dengan menghapus barrier to entry pada sektor usaha yang selama ini dimonopoli pemerintah dan tertutup bagi modal asing.
Gelombang liberalisasi dalam pembangunan perekonomian nasional kembali berlangsung pasca krisis moneter tahun 1997-1998 ketika pemerintah Indonesia sepakat dengan resep IMF untuk melakukan kebijakan privatisasi, pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan serta reformasi sistem perbankan pada akhir Oktober 1997 sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman USD 40 M.
Paket kebijakan deregulasi, swastanisasi dan minimalisasi peran negara yang disepakati dengan IMF ini tidak bisa dipungkiri merupakan bentuk operasional dari doktrin ekonomi liberal sebagaimana dinyatakan dalam Washington Concencus, yang disiapkan bagi negara-negara berkembang, terutama negara Amerika Latin (Vaut dan Simon: 2014).
UU Cipta Kerja yang sangat pro terhadap modal asing dapat dilihat sebagai gelombang lanjutan dari kebijakan ekonomi politik yang berhaluan liberal.
Pandangan ekonomi alternatif
UU Omnibus law sudah disahkan pemerintah. Pihak yang kontra sudah melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ada enam pengajuan judicial review terkait UU Omnibus Law ini, sebagaimana terlihat dalam web site Mahkamah Konstitusi.
Kita tidak tahu apakah gugatan ini akan dikabulkan seluruhnya, sebagian atau malah ditolak MK. Tetapi, ada beberapa masukan substansif yang perlu diperhatikan terkait dengan UU Omnibus law ini.
Kebijakan ekonomi liberal yang didasari asumsi bahwa kesejahteraan masyarakat akan terjadi seiring dengan kemajuan ekonomi, yang berdampak pada trickle down effect sebagaimana di anut Orde Baru, tidak sesuai dengan kenyataan.
Liberalisasi ekonomi memang meningkatkan ekonomi Indonesia. Tetapi itu tidak diikuti dengan kesejahteraan sebagian besar masyarakatnya. Peningkatan ekonomi hanya dialami para pengusaha besar.
Idealnya, pembangunan dan peningkatan ekonomi juga dibarengi dengan pemerataan ekonomi. Ini yang menjadi kritik dari Joseph E. Stiglitz dan Amartya Sen.
Mereka tidak setuju dengan kebijakan yang melihat indikator kesejahteraan hanya dalam masalah produksi dan PDB, di mana produksi diasumsikan berbanding lurus dengan penciptaan pasar dan lapangan kerja.
Tentu saja, indikator tersebut tidak diabaikan, tetapi Stiglitz dan Amartya Sen melihat indikator persoalan kesejahteraan dengan lebih holisitik di mana aspek konsumsi rumah tangga, distribusi kekayaan dan pemerataan pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup menjadi hal yang diperhatikan.
Bagaimana melengkapi efisiensi pasar dengan pemerataan atau keadilan sosial dan perspektif yang lebih holistik tentang kesejahteraan, merupakan pekerjaan rumah besar pemerintahan Jokowi yang tersisa kurang dari 4 tahun lagi.
Rasanya, ini masukan penting yang perlu didengar pemerintah Jokowi. Aturan turunan UU Cipta Kerja perlu mengakomodir hal ini, lepas apakah putusan MK menerima atau menolak judicial review yang sedang berjalan.
Syafril Efendi
Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia